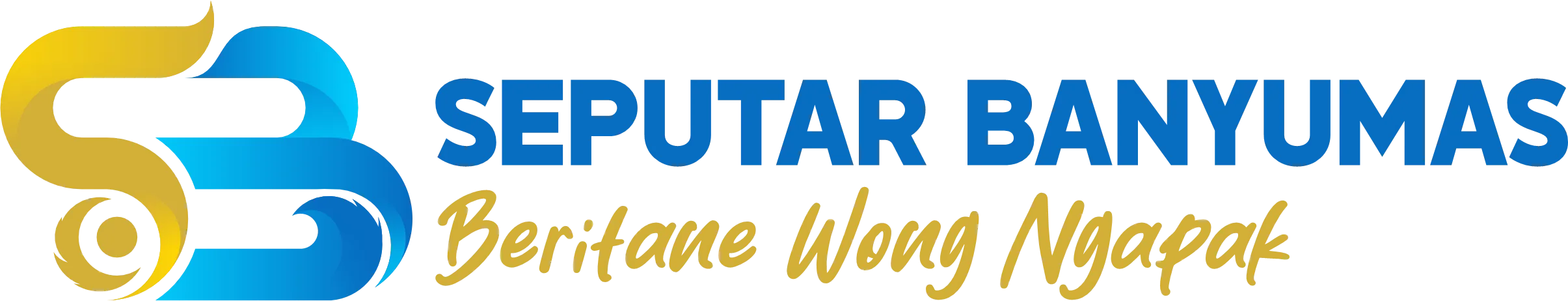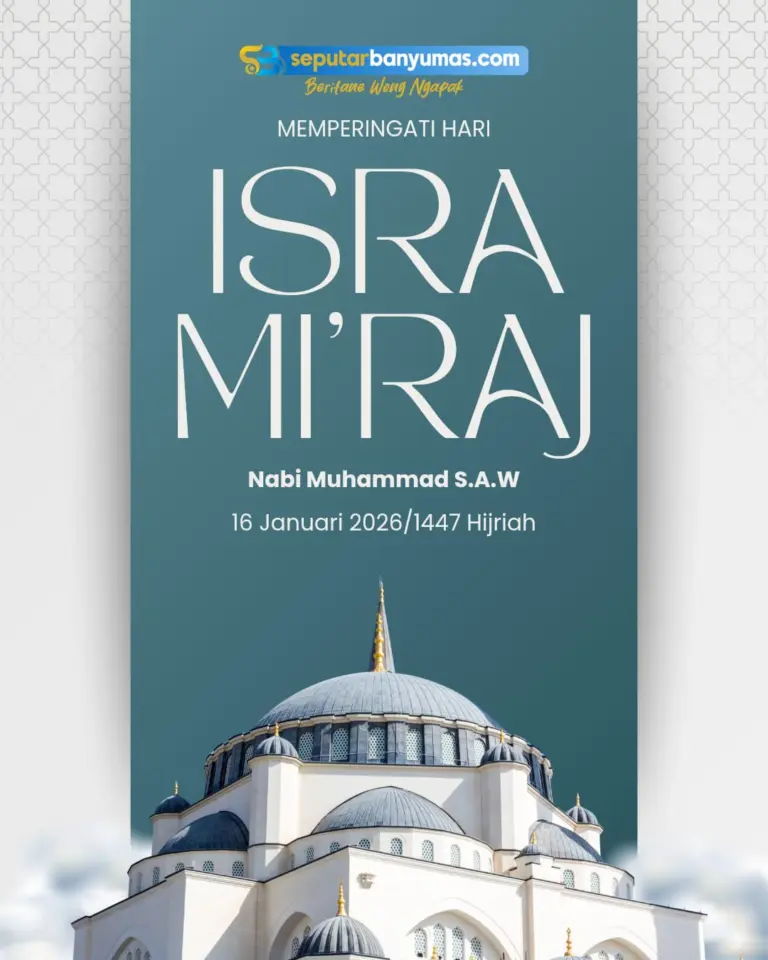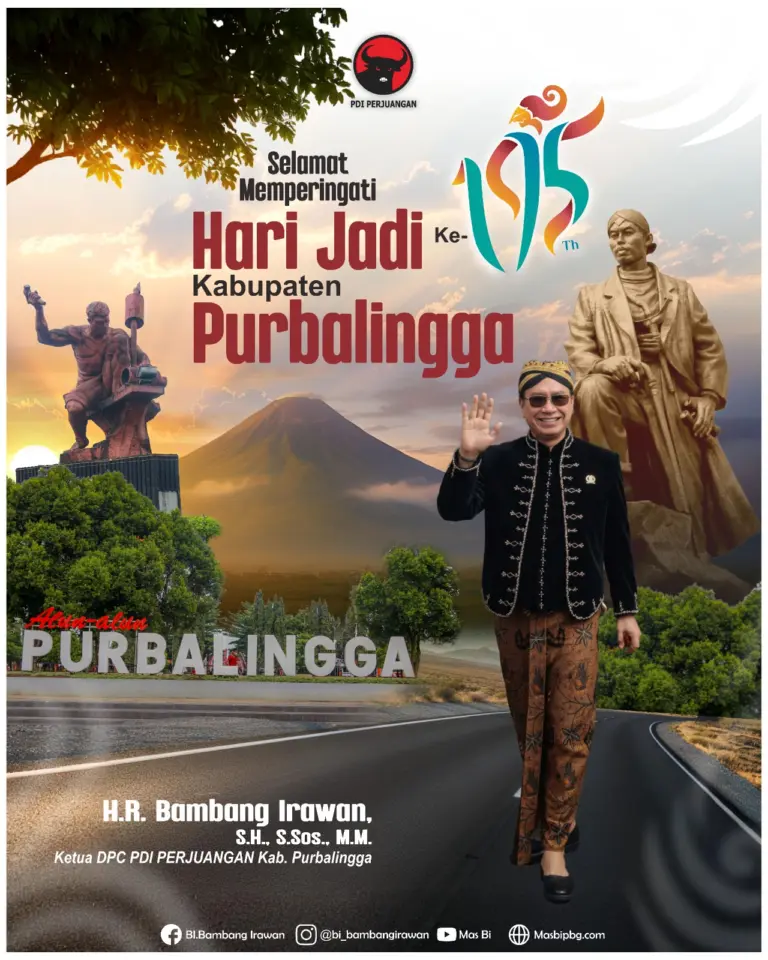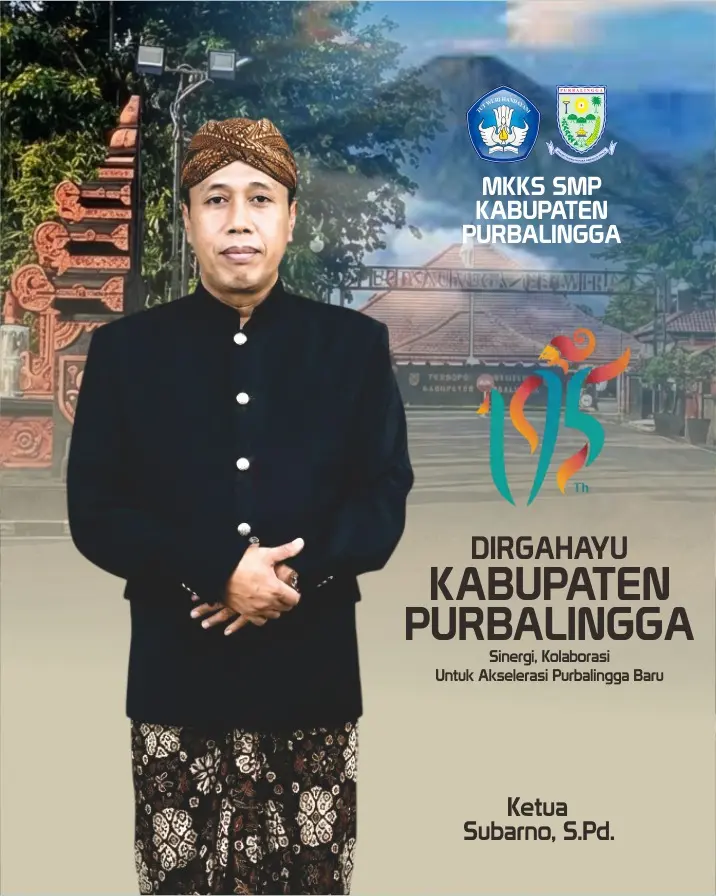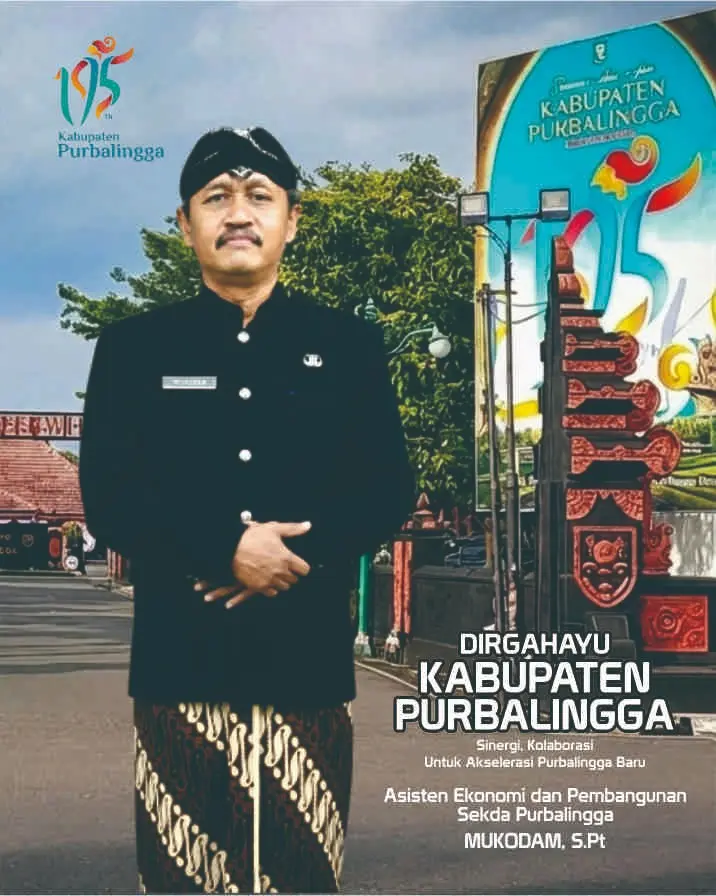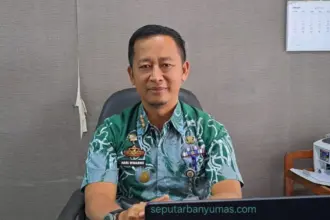SEPUTARBANYUMAS.COM – Pemberian amnesti kepada 1.116 narapidana oleh Presiden Prabowo Subianto menandai babak baru dalam diskursus hukum dan keadilan di Indonesia. Bukan sekadar kebijakan politis atau bentuk belas kasihan negara, amnesti kali ini membawa pesan moral kuat: bahwa hukum tidak boleh kehilangan arah, dan keadilan tidak bisa sekadar diukur dari ketaatan pada teks.
“Amnesti ini bukan hadiah populis. Ini adalah rem darurat atas potensi disorientasi hukum,” tulis narasi resmi yang menyertai kebijakan tersebut. Banyak di antara penerima amnesti adalah narapidana non-kekerasan—pengguna narkoba yang seharusnya direhabilitasi, warga dengan gangguan kejiwaan, hingga pelanggar pasal karet seperti ITE yang hanya mengungkapkan aspirasi lewat satire politik.
Krisis Sistemik: Antara Overcrowding dan Overkriminalisasi
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia saat ini menggambarkan kegagalan struktural dalam praktik pemidanaan. Dengan daya tampung hanya 146.260 orang, per Agustus 2025, jumlah penghuni lapas tembus 281.743 orang. Rasio petugas dengan warga binaan bahkan mencapai 1:80 di sejumlah wilayah—angka yang mencerminkan ketimpangan besar dalam pelayanan, pembinaan, dan keamanan.
Namun overcrowding hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya adalah overkriminalisasi, yaitu kecenderungan memenjarakan semua bentuk penyimpangan sosial tanpa membedakan konteks dan risiko. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan, lebih dari 53% penghuni lapas adalah pelaku tindak pidana narkotika, mayoritas dari mereka adalah pengguna non-kekerasan.
“Negara seolah tak mampu membedakan siapa yang harus dihukum dan siapa yang harus dipulihkan,” jelas narasi tersebut. Dalam kerangka ini, amnesti bukan berarti menghapus kesalahan, tapi mengembalikan kesadaran hukum agar lebih adil dan manusiawi.
Amnesti Sebagai Jalan Etis
Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 memang memberikan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan amnesti, dengan pertimbangan DPR. Namun lebih dari aspek legal, kebijakan ini adalah bentuk koreksi etis. Ia mempertanyakan logika penghukuman yang selama ini lebih menekankan balas dendam ketimbang reintegrasi sosial.
Filsuf hukum John Rawls pernah menyatakan bahwa keadilan adalah soal fairness, bukan hanya legalitas. Dalam kerangka ini, amnesti berfungsi sebagai mekanisme evaluasi kolektif: Apakah hukum telah menjalankan fungsinya secara adil, atau justru memperkuat ketidakadilan struktural?
Menyongsong Reformasi Hukum Pidana
Pemberlakuan KUHP baru pada Januari 2026 membuka peluang besar bagi reformasi sistem pemidanaan. Prinsip ultimum remedium, pidana alternatif seperti kerja sosial dan denda harian, serta pendekatan restoratif mulai diakomodasi. Dalam skema baru ini, peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) akan semakin sentral sebagai penghubung antara tahap pra-adjudikasi hingga reintegrasi sosial.
Namun perubahan teks hukum tak akan cukup tanpa perubahan budaya hukum. “Selama hukum progresif tidak ditopang imajinasi sosial yang baru, penjara akan tetap penuh dan keadilan akan terus berarti penderitaan,” tulis narasi reflektif tersebut.
Amnesti sebagai Awal, Bukan Akhir
Keputusan Presiden Prabowo memberi amnesti harus dibaca sebagai titik tolak. Ia adalah bentuk keberanian negara untuk mengakui bahwa keadilan bukan sekadar soal menghukum, tapi soal memulihkan. Di tengah budaya hukum yang masih kuat dipengaruhi logika kolonial dan balas dendam, amnesti ini menjadi sinyal perubahan arah menuju sistem hukum yang lebih berkeadilan secara substansi.
“Amnesti adalah langkah pertama untuk menyelamatkan bukan hanya mereka yang terpenjara, tetapi juga martabat hukum itu sendiri,” demikian kutipan penutup yang menyiratkan pesan penting: bahwa negara yang adil adalah negara yang berani mengoreksi dirinya.