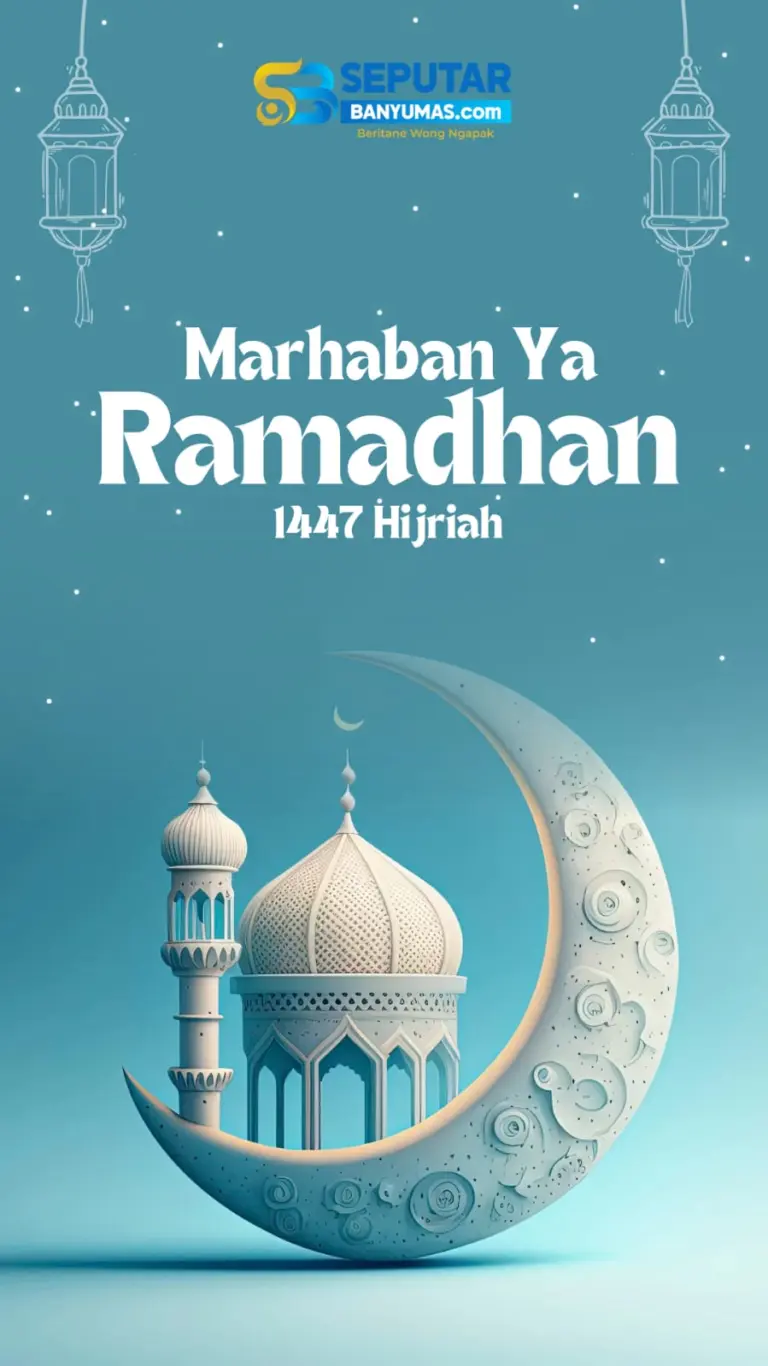Adzan berkumandang, namun bagi banyak dari kita yang mangaku sebagai umat muslim, suara itu tidak lagi terdengar seperti undangan cinta, melainkan alarm yang mendesak. Ada sebuah ruang sunyi di antara lisan yang bersyahadat dan kaki yang berat melangkah menuju kiblat. Kita terjebak dalam sebuah paradoks: mengakui Tuhan sebagai pusat kehidupan, namun menempatkan perjumpaan dengan-Nya sebagai beban yang menyela kesibukan.
Di banyak sudut kehidupan hari ini, kita menemukan pemandangan yang sunyi namun nyata: Muslim yang lisannya fasih menyebut iman, tetapi langkah kakinya terasa berat saat adzan berkumandang. Tidak ada yang berteriak, tidak ada yang menunjuk, namun realitas itu hadir seperti bayangan—tenang, tapi mengusik nurani.
Paradoks ini bukan cerita tentang siapa yang salah atau siapa yang paling benar. Ini adalah potret bersama, cermin yang diam-diam memantulkan wajah kita sendiri. Iman tetap diakui, syahadat tetap dijaga, tetapi shalat perlahan bergeser dari kebutuhan jiwa menjadi kewajiban yang terasa membebani.
Banyak Muslim hari ini hidup dalam ritme yang melelahkan. Pagi diburu target, siang ditelan kesibukan, malam dikuras keletihan. Di tengah hiruk-pikuk itu, shalat sering datang seperti “interupsi”—bukan perjumpaan, bukan pelepas, melainkan jeda yang dianggap mengganggu alur hidup.
Padahal shalat tidak pernah meminta lebih dari kejujuran hati. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya kehadiran. Namun justru di situlah masalahnya: menghadirkan hati jauh lebih berat daripada sekadar menggerakkan tubuh. Kita mampu berdiri, rukuk, sujud, tetapi hati tertinggal entah di mana.
Fenomena ini sering lahir bukan karena kebencian pada shalat, melainkan karena kelelahan batin yang tak disadari. Jiwa yang lama tak disapa, iman yang jarang dirawat, membuat ibadah terasa kering. Seperti orang kehausan yang lupa bahwa airlah yang ia butuhkan.
Di sisi lain, dunia menawarkan ribuan alasan untuk menunda. Notifikasi lebih cepat dari adzan, deadline terasa lebih mendesak daripada panggilan langit. Perlahan, prioritas pun bergeser, bukan karena sengaja, tapi karena terbiasa.
Ironisnya, banyak yang tetap merasa “baik-baik saja”. Identitas Muslim tetap melekat, nilai-nilai agama tetap dibicarakan, tetapi hubungan personal dengan Allah menjadi formal dan berjarak. Shalat tetap dilakukan—atau ditinggalkan—tanpa rasa kehilangan.
Inilah paradoks itu: iman diyakini sebagai kebenaran, tetapi tidak selalu dirasakan sebagai kebutuhan. Padahal, shalat tidak diturunkan untuk membebani hidup, melainkan untuk menopangnya. Ia bukan beban, tetapi penyangga; bukan tugas, tetapi tempat kembali.
Saat shalat terasa berat, mungkin yang perlu ditanya bukan “mengapa aku malas?”, melainkan “apa yang sedang lelah dalam diriku?”. Bisa jadi iman tidak mati, hanya tertutup debu panjangnya perjalanan hidup.
Ada Muslim yang rindu kepada Allah, tetapi tidak tahu bagaimana cara kembali mendekat. Ada yang ingin khusyuk, tetapi pikirannya penuh. Ada yang ingin taat, tetapi hatinya kosong. Semua itu manusiawi, dan justru di sanalah pintu perbaikan terbuka.
Shalat yang hidup lahir dari iman yang disirami, bukan dipaksa. Ia tumbuh dari pemahaman, bukan sekadar hafalan. Ketika shalat dipahami sebagai dialog, bukan formalitas, beban perlahan berubah menjadi kebutuhan yang dirindukan.
Jurnalisme kehidupan hari ini mencatat satu hal penting: krisis umat bukan semata kurangnya ibadah, tetapi melemahnya makna ibadah. Kita melakukan banyak hal, namun lupa menghidupkan ruhnya. Kita bergerak cepat, tetapi kehilangan arah pulang.
Paradoks Muslim ini bukan vonis, melainkan undangan halus untuk merenung. Bahwa mungkin, di balik rasa berat itu, Allah sedang memanggil dengan cara yang paling lembut: “Datanglah, bukan karena kewajibanmu, tapi karena engkau butuh Aku.”
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!