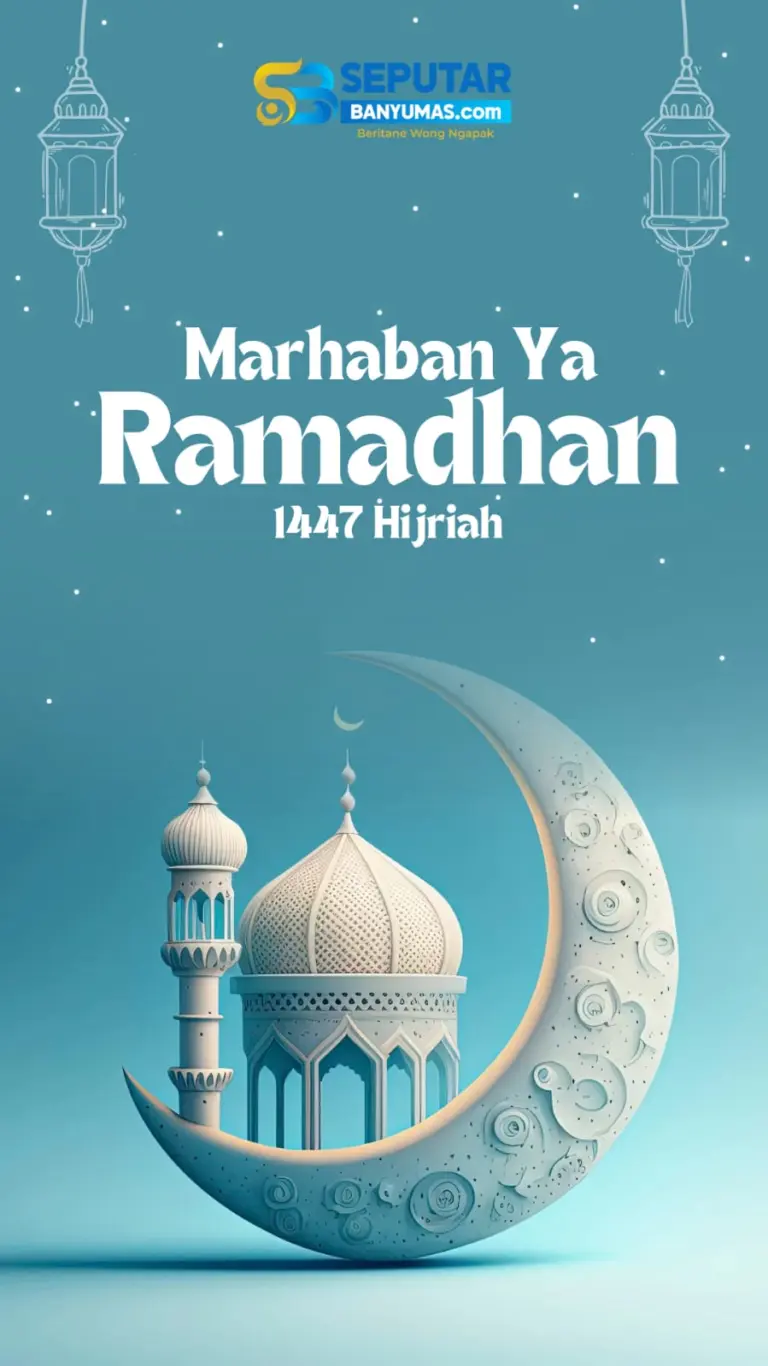Banyak dari kita yang dengan fasih menyebut ngerinya api Jahannam, pedihnya azab kubur, hingga siksa neraka yang tak terbayangkan. Namun, sebuah fenomena miris justru sering terjadi di depan mata.
Meski lisan mengaku takut, kaki seolah tetap ringan melangkah menuju maksiat, dan tangan masih saja gemar berbuat dosa. Di sinilah paradoks itu bermula: Kita seolah ‘berani’ melanggar perintah Allah sementara hati terasa biasa-biasa saja. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Kita gemetar ketika mendengar ceramah tentang siksa neraka, tetapi tenang saat menunda shalat. Kita tersentuh ketika ayat azab dibacakan, tetapi santai saat menipu, berbohong, atau menyakiti sesama. Seakan-akan dosa telah menjadi teman akrab, bukan musuh yang harus dihindari.
Ketakutan kita sering kali lebih bersifat emosional sesaat, bukan kesadaran yang mengubah arah hidup. Air mata bisa jatuh di majelis ilmu, namun mengering begitu keluar dari masjid. Hati tersentuh, tetapi tidak menetap. Takut, tetapi tidak cukup kuat untuk taat.
Akar masalahnya sering tersembunyi: kita mengenal neraka, tetapi belum benar-benar mengenal Allah. Takut azab-Nya, namun belum mencintai perintah-Nya. Padahal, ketaatan sejati lahir dari cinta yang mendalam, bukan sekadar rasa takut yang dangkal.
Ada dosa-dosa yang kita anggap kecil, padahal terus diulang. Kita berkata, “Ini hanya sekali,” lalu mengulanginya berkali-kali. Dosa yang diremehkan itulah yang perlahan mengeraskan hati, hingga maksiat terasa biasa dan taat terasa berat.
Lebih berbahaya lagi, ketika kita pandai mencari pembenaran. Kita tahu itu salah, tapi selalu punya alasan: keadaan, tekanan, atau dalih “semua orang juga begitu.” Pembenaran adalah pintu masuk paling halus menuju kebiasaan dosa.
Takut Siksa Neraka Harusnya Lahirkan Kewaspadaan
Kita lupa bahwa rasa takut kepada siksa neraka seharusnya melahirkan kewaspadaan, bukan sekadar kekhawatiran kosong. Takut yang benar akan membuat seseorang menjauh, bukan mendekat. Jika api terasa panas, tak mungkin kita mendekat dengan santai.
Ironisnya, kita takut mati dalam keadaan buruk, tetapi hidup dengan kebiasaan buruk. Kita berharap husnul khatimah, namun istiqamah dalam maksiat. Padahal akhir kehidupan sering kali cerminan dari kebiasaan sepanjang hidup.
Allah Maha Pengampun, benar. Namun rahmat-Nya bukan alasan untuk berani bermaksiat. Pengampunan Allah adalah harapan bagi yang bertaubat, bukan tameng bagi yang sengaja berbuat dosa.
Paradoks ini harus diakhiri dengan kejujuran pada diri sendiri. Berani bertanya: apakah ketakutan ini sungguh-sungguh, atau hanya rasa tidak nyaman sesaat? Apakah iman ini hidup, atau sekadar identitas?
Taubat bukan hanya berhenti, tetapi berbalik arah. Bukan sekadar menyesal, tetapi membangun jarak dengan dosa. Bukan hanya menangis, tetapi bertekad untuk berubah, meski perlahan dan tertatih.
Kita tidak diminta menjadi malaikat dalam semalam. Tetapi kita diminta untuk jujur dalam perjuangan. Jatuh boleh, asal bangkit. Tersandung boleh, asal tidak betah berlama-lama di jalan maksiat.
Ketika rasa takut bertemu dengan cinta kepada Allah, di situlah iman menemukan keseimbangannya. Takut membuat kita waspada, cinta membuat kita rindu untuk taat. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
Jangan tunggu dosa menjadi kebiasaan, baru ingin berubah. Jangan tunggu hati mati rasa, baru ingin hidup. Siksa neraka bukan sekadar cerita untuk ditakuti, tetapi peringatan agar kita kembali sebelum terlambat.
Semoga kita tidak lagi menjadi Muslim yang paradoks: takut Siksa neraka, tapi akrab dengan dosa. Semoga ketakutan itu berubah menjadi ketaatan, kegelisahan menjadi kesungguhan, dan iman yang rapuh menjadi iman yang hidup—yang menuntun langkah kita pulang kepada Allah.
*Anda bisa lebih lihat info lain di Instagram kami.