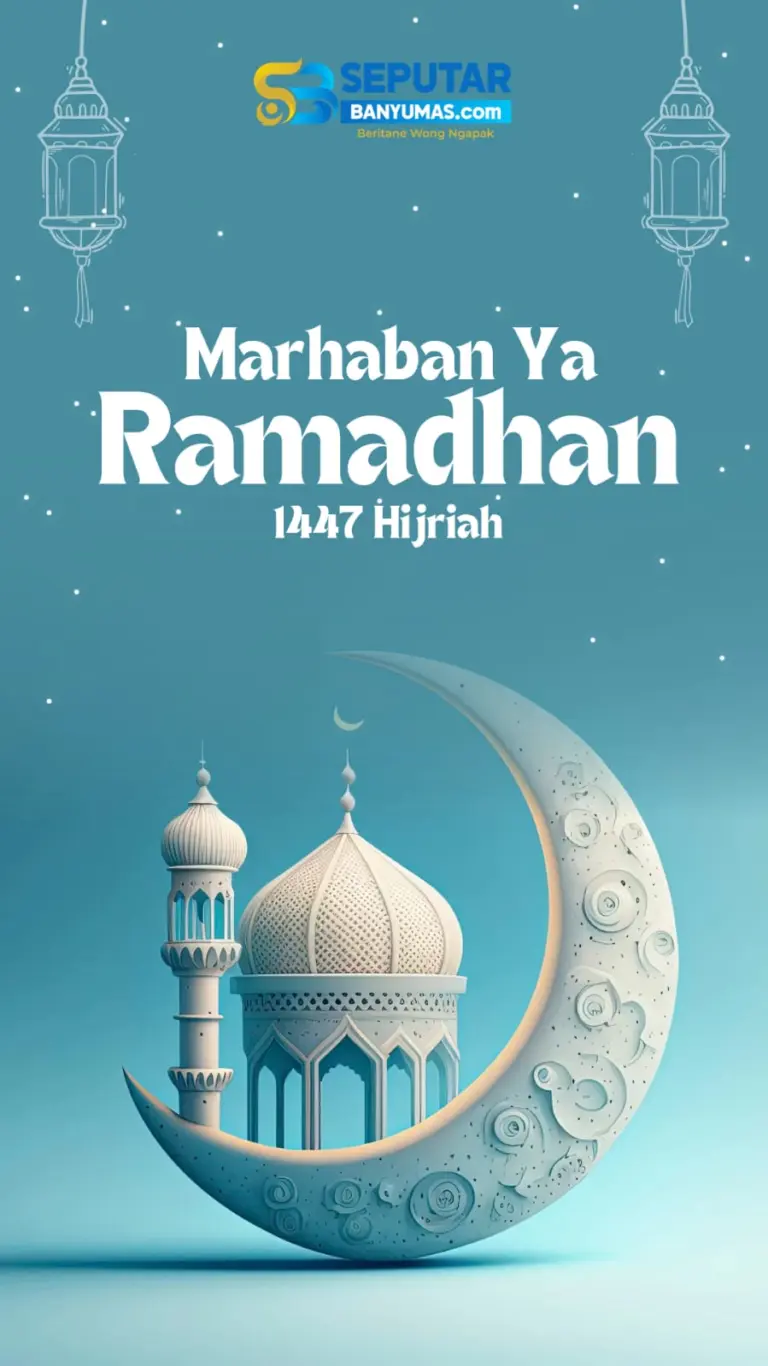Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ‘anhu bukanlah manusia yang lemah, tetapi hatinya terlalu hidup untuk dibuat keras oleh dunia. Ia menangis bukan karena tak sanggup menanggung beban kehidupan, melainkan karena takut imannya berkurang walau sedikit. Di saat banyak orang hari ini bangga dengan tawa di atas kelalaian, Abu Bakar justru gemetar oleh rasa takut kepada Allah. Ironisnya, kita sering merasa baik-baik saja meski shalat terasa hambar dan Al-Qur’an jarang disentuh.
Abu Bakar memiliki semua yang sering kita kejar: harta, kehormatan, jaringan, dan masa depan yang mapan. Namun ia tidak menjadikan itu semua sebagai alasan untuk menunda kebenaran. Ketika Islam datang, ia tidak berkata, “Tunggu aku siap,” atau “Aku pikirkan dulu risikonya.” Ia langsung membenarkan. Bandingkan dengan kita yang sering menunda taubat dengan alasan belum siap, padahal kematian tidak pernah menunggu kesiapan siapa pun.
Tangisan Abu Bakar adalah sindiran keras bagi generasi yang terlalu kering air mata. Ia menangis saat membaca Al-Qur’an, sedangkan kita sering membaca tanpa rasa, bahkan sambil mengejar notifikasi. Hatinya gemetar karena ayat-ayat Allah, sementara hati kita justru lebih bergetar oleh pujian manusia. Abu Bakar takut amalnya ditolak, kita justru sibuk menghitung amal orang lain.
Ketika Abu Bakar menginfakkan hartanya untuk Islam, ia tidak sibuk memamerkan keikhlasan. Ia membebaskan budak-budak yang disiksa karena iman, bukan untuk membangun citra, tetapi karena keyakinan bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Hari ini, sebagian kita pelit pada dakwah, namun royal untuk gaya hidup. Kita bangga dengan label “umat akhir zaman” sambil tetap ingin hidup seperti penduduk dunia yang abadi.
Perjalanan hijrah menjadi cermin besar tentang prioritas hidup. Abu Bakar menemani Rasulullah ﷺ dalam kondisi paling berbahaya. Di Gua Tsur, ia menangis bukan karena takut mati, tetapi karena takut Rasulullah ﷺ terluka. Sementara kita hari ini sering takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan posisi, takut kehilangan relasi, tapi tidak terlalu takut kehilangan Allah. Kita menyebut diri beriman, namun masih menghitung pengorbanan.
Yang lebih menampar hati adalah akhir kehidupan Abu Bakar. Ia menangis menjelang wafat, bukan karena meninggalkan dunia, sebab dunia sudah lama ia tinggalkan. Ia menangis karena takut apakah amalnya diterima. Padahal ia sahabat terbaik Nabi ﷺ, khalifah pertama, dan manusia yang dijamin surga. Jika Abu Bakar saja masih takut, lalu di mana posisi rasa aman kita yang penuh dosa namun merasa baik-baik saja?
Abu Bakar tidak sibuk membangun warisan materi. Ia membangun warisan iman. Ia wafat dalam kesederhanaan, tanpa istana, tanpa kemewahan. Dunia tidak menempel di tangannya, apalagi di hatinya. Kita sebaliknya, sering menempelkan dunia ke dada, lalu heran mengapa hati terasa sempit dan hidup terasa berat.
Kisah Abu Bakar menyindir kita yang sering mengukur keberhasilan dengan angka, jabatan, dan pengakuan. Padahal ukuran sejati adalah sejauh mana hati kita takut kepada Allah saat sendiri, sejauh mana air mata masih bisa jatuh karena dosa, dan sejauh mana dunia bisa kita lepaskan saat Allah memanggil. Abu Bakar besar bukan karena hartanya, tetapi karena keberaniannya melepaskan.
Abu Bakar mengajarkan bahwa iman bukan sekadar slogan, tetapi keputusan hidup. Keputusan untuk jujur meski rugi, taat meski berat, dan istiqamah meski sepi. Ia menangis karena sadar hidup ini singkat dan hisab itu pasti. Kita sering tertawa seolah hidup panjang dan pertanggungjawaban bisa ditunda.
Jika hari ini iman terasa lelah, jangan buru-buru menyalahkan zaman. Mungkin hati kita terlalu penuh oleh dunia. Belajarlah dari Abu Bakar: kurangi genggaman pada dunia agar hati bisa menggenggam Allah. Sebab pada akhirnya, yang akan menyelamatkan kita bukan apa yang kita miliki, tetapi apa yang rela kita tinggalkan demi Allah. Dan di situlah, tangis Abu Bakar berubah menjadi cahaya bagi siapa pun yang ingin pulang dengan selamat.
Follow akun sosial media kami untuk update berita terbaru!