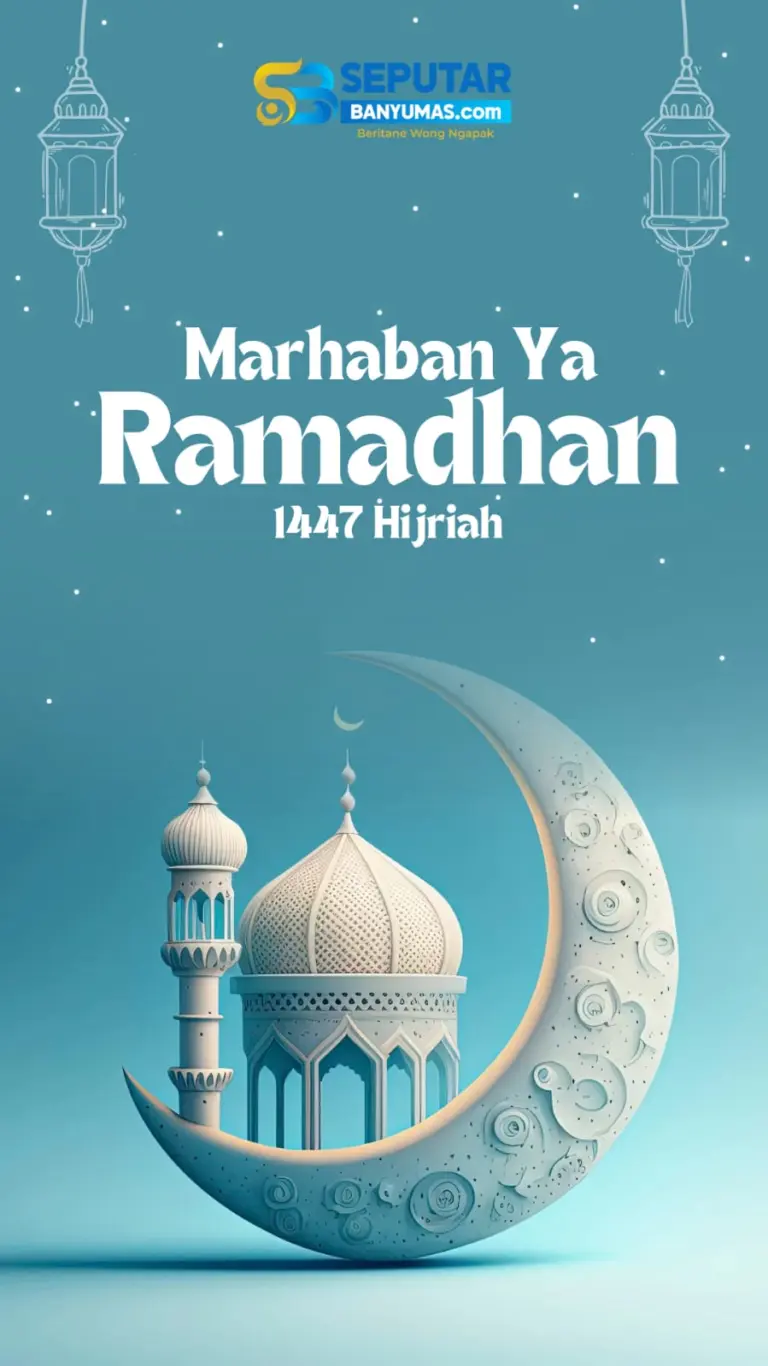Di tengah sejarah yang dipenuhi nama-nama besar dan kekuasaan yang gemerlap, Umar bin Khattab berdiri sebagai sosok yang justru gemetar bukan karena musuh, tetapi karena tangisan rakyatnya. Ia adalah khalifah kedua kaum Muslimin, penguasa wilayah yang membentang luas dari Jazirah Arab hingga Persia. Namun, di balik kekuatan dan ketegasannya, Umar menyimpan satu ketakutan terbesar: takut jika ada rakyat yang lapar, terzalimi, atau menangis karena kelalaiannya.
Umar bin Khattab bukan sekadar pemimpin politik. Ia adalah pemimpin ruhani, pemimpin nurani, dan pemimpin yang memikul amanah dengan rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Baginya, jabatan bukan kemuliaan, melainkan beban yang akan ditanya satu per satu di hadapan Allah kelak. Karena itulah, setiap malam Umar berkeliling kota Madinah, menyamar, menyusuri lorong-lorong gelap, memastikan tidak ada rakyat yang tidur dalam kelaparan.
Salah satu kisah paling menggetarkan hati adalah ketika Umar mendengar tangisan anak kecil di tengah malam. Ia mendekat dan mendapati seorang ibu yang sedang merebus batu. Bukan karena hendak memasak, tetapi untuk menenangkan anaknya agar mengira makanan sedang disiapkan. Ketika Umar bertanya, sang ibu menjawab dengan jujur bahwa mereka kelaparan, dan bahkan melontarkan keluhan, “Semoga Allah mengadili Umar, karena ia lalai terhadap kami.”
Umar tidak marah. Tidak membela diri. Tidak menyebut bahwa ia adalah khalifah. Justru tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh. Ia berkata dalam hatinya, “Celakalah Umar, bagaimana jika Allah benar-benar mengadili aku karena kelalaian ini?” Malam itu juga, Umar memanggul sendiri karung gandum dari Baitul Mal. Ketika pembantunya menawarkan bantuan, Umar menolak sambil berkata, “Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?”
Inilah Umar bin Khattab. Pemimpin yang takut kepada tangisan rakyat lebih dari takut kehilangan kekuasaan. Pemimpin yang memahami bahwa amanah bukan tentang duduk di singgasana, tetapi tentang melayani mereka yang paling lemah.
Umar dikenal tegas, bahkan keras dalam menegakkan keadilan. Namun ketegasan itu tidak pernah lahir dari keangkuhan, melainkan dari rasa takut kepada Allah. Ia pernah berkata, “Seandainya ada seekor keledai terperosok di Irak, aku takut Allah akan bertanya kepadaku, mengapa aku tidak meratakan jalan untuknya.” Kalimat ini bukan hiperbola, tetapi cerminan hati seorang pemimpin yang sadar bahwa setiap penderitaan rakyat adalah tanggung jawab penguasa.
Dalam kepemimpinannya, Umar hidup sangat sederhana. Pakaiannya penuh tambalan. Makanannya kasar. Rumahnya tak mewah. Ia tidak ingin hidup lebih nyaman dari rakyatnya. Baginya, bagaimana mungkin seorang pemimpin menikmati kelezatan dunia sementara rakyatnya menderita? Prinsip ini begitu kontras dengan wajah kepemimpinan di banyak zaman, termasuk hari ini, ketika sebagian pemimpin justru berlomba-lomba menumpuk kemewahan di atas penderitaan masyarakat.
Umar bin Khattab Terbuka Dikritik
Umar juga dikenal sebagai pemimpin yang terbuka terhadap kritik. Suatu hari, seorang wanita menegurnya di depan umum dalam persoalan mahar. Umar tidak tersinggung. Ia tidak menggunakan kekuasaannya untuk membungkam suara rakyat. Ia justru berkata, “Wanita itu benar, Umar yang salah.” Kerendahan hati seperti inilah yang membuat kepemimpinannya dicintai, bukan ditakuti.
Ketakutan Umar bukanlah ketakutan yang melemahkan, melainkan ketakutan yang melahirkan keadilan, empati, dan kerja nyata. Ia takut kepada Allah, maka ia berani kepada kezaliman. Ia takut kepada hisab, maka ia tidak berani bermain-main dengan amanah. Ia takut mendengar tangisan rakyat, maka ia memilih berjaga di malam hari daripada tidur nyenyak.
Dalam dunia modern yang sering mengagungkan kepemimpinan berbasis citra, Umar mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari nurani, bukan dari pencitraan. Ia tidak sibuk membangun narasi tentang keberhasilannya, tetapi sibuk memastikan tidak ada satu pun rakyat yang terabaikan. Ia tidak menunggu laporan di istana, tetapi turun langsung ke lapangan.
Umar bin Khattab wafat bukan sebagai penguasa yang bergelimang harta, tetapi sebagai hamba Allah yang penuh luka amanah. Bahkan di akhir hayatnya, ia masih bertanya, “Apakah aku termasuk orang yang selamat atau binasa?” Padahal sejarah mencatatnya sebagai salah satu pemimpin paling adil yang pernah ada. Inilah puncak ketakwaan: tak pernah merasa aman dari hisab Allah, meski telah berbuat begitu banyak kebaikan.
Kisah Umar bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin tajam bagi siapa pun yang memegang amanah, baik sebagai pemimpin negara, pemimpin organisasi, orang tua, guru, atau siapa pun yang bertanggung jawab atas orang lain. Umar mengajarkan bahwa amanah sekecil apa pun akan dimintai pertanggungjawaban, dan keadilan bukan slogan, tetapi pengorbanan.
Di zaman ketika tangisan rakyat sering tenggelam oleh sorak kekuasaan, sosok Umar bin Khattab hadir sebagai pengingat bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang tidak tega mendengar penderitaan rakyatnya. Pemimpin sejati bukan yang paling dielu-elukan, tetapi yang paling takut kepada Allah dan paling peduli kepada manusia.
Semoga kisah Umar bin Khattab tidak hanya menggetarkan hati kita, tetapi juga membangunkan nurani kita. Karena sejatinya, setiap kita adalah pemimpin. Dan pertanyaannya bukanlah seberapa tinggi jabatan kita, tetapi apakah kita peka terhadap tangisan orang-orang yang Allah titipkan di sekitar kita.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.