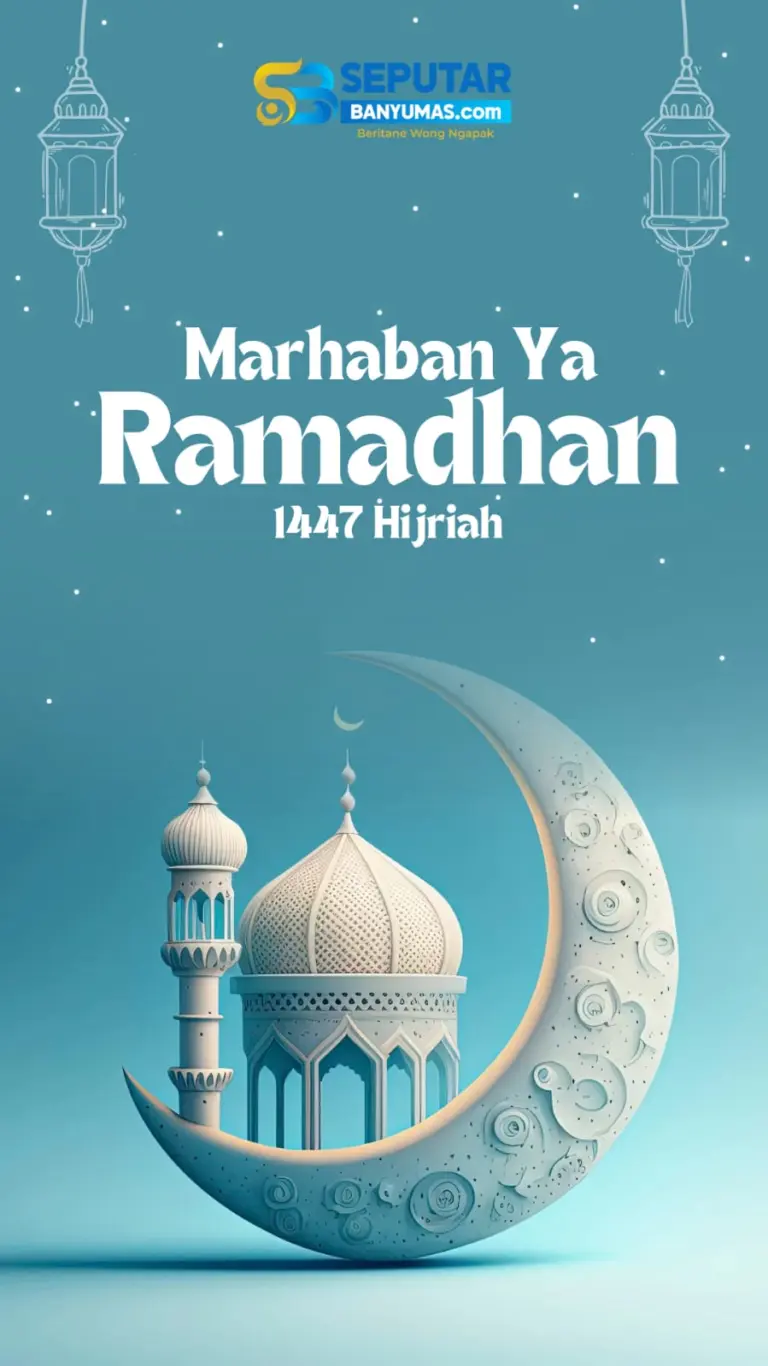Di Makkah, sebelum Islam berdiri tegak, nama Mus’ab bin Umair adalah simbol kemewahan. Ia dikenal sebagai pemuda paling rapi, paling harum, dan paling memesona di kota itu. Setiap langkahnya mengundang decak kagum. Pakaiannya dari sutra terbaik Yaman, sandalnya dari kulit pilihan, minyak wangi yang melekat di tubuhnya membuat orang tahu: Mus’ab baru saja lewat.
Ia lahir dari keluarga bangsawan Quraisy di Makkah, hidup dalam limpahan harta, dimanja ibunya, Khunais binti Malik, seorang wanita terpandang yang tak pernah membiarkan anaknya kekurangan apa pun. Namun sejarah tidak selalu memilih orang yang nyaman untuk memikul risalah. Allah memilih hati yang berani.
Segalanya berubah ketika Mus’ab diam-diam mendengar kabar tentang seorang Nabi di Darul Arqam. Ada getaran aneh dalam dadanya. Ia datang, mendengar Al-Qur’an dibacakan Rasulullah ﷺ, dan saat itu juga hatinya runtuh—bukan karena takut, tapi karena kebenaran.
Kalimat-kalimat wahyu menembus lapisan kemewahan yang selama ini membungkus jiwanya. Mus’ab bersyahadat. Tanpa sorak. Tanpa pesta. Hanya langit yang menjadi saksi.
Keislamannya disembunyikan, bukan karena ragu, tetapi karena tahu badai apa yang akan datang. Namun rahasia selalu menemukan jalannya untuk terbongkar. Ketika ibunya tahu, cinta yang dahulu hangat berubah menjadi cambuk. Mus’ab dikurung, disiksa, diputus dari segala fasilitas. Sutra diganti karung kasar. Harum diganti bau debu dan luka. Tapi ada yang tak bisa direnggut siapa pun darinya: iman.
Ibunya mengancam, memohon, merayu, bahkan bersumpah tidak akan makan dan minum. “Pilih aku atau agama barumu,” katanya. Mus’ab menatap dengan mata basah namun tegas. “Wahai ibu, seandainya engkau memiliki seratus nyawa dan satu per satu keluar di hadapanku, aku tidak akan meninggalkan agama ini.” Saat itu, seorang ibu kehilangan anak kebanggaannya. Dan Islam mendapatkan seorang pejuang sejati.
Mus’ab hijrah ke Habasyah. Lalu kembali. Lalu hijrah lagi. Setiap hijrah adalah pengelupasan diri dari dunia. Hingga suatu hari Rasulullah ﷺ mengutusnya ke Yatsrib—sebuah kota yang belum sepenuhnya mengenal Islam—sebagai duta pertama. Bukan Umar yang gagah. Bukan Hamzah yang ditakuti. Tapi Mus’ab, pemuda lembut, berakhlak halus, penuh hikmah.
Selepas Mus’ab Kembali ke Makkah
Di Yatsrib, Mus’ab tidak datang membawa pedang. Ia datang membawa Al-Qur’an. Ia duduk, berbicara, mendengar, menjelaskan. Dengan kesabaran dan kecerdasan, ia menyentuh hati para pemimpin kabilah. Sa’ad bin Mu’adz dan Usaid bin Hudhair masuk Islam lewat lisannya.
Dari satu rumah ke rumah lain, Islam menyala. Ketika Mus’ab kembali ke Makkah, hampir tak ada rumah Anshar yang tidak mengenal Islam. Rasulullah ﷺ tersenyum bangga. Inilah hasil dakwah tanpa gemerlap.
Tahun-tahun berlalu. Perang Uhud meletus. Mus’ab membawa panji kaum Muslimin. Di medan perang, ia berdiri tegak seperti gunung. Ketika barisan kacau, panji hampir jatuh, Mus’ab maju ke depan. Satu tebasan memutus tangan kanannya.
Ia memindahkan panji ke tangan kiri. Tangan kiri pun tertebas. Ia mendekap panji dengan sisa tubuhnya, sambil berseru, “Muhammad hanyalah seorang Rasul; sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul.” Hingga tombak musuh menembus dadanya. Mus’ab roboh. Panji tetap terjaga. Iman tetap berdiri.
Perang usai. Rasulullah ﷺ berjalan menyusuri medan Uhud. Ketika sampai di hadapan jenazah Mus’ab, beliau terdiam. Air mata jatuh. Di hadapan Nabi, terbujur tubuh yang dulu paling mewah di Makkah—kini tak memiliki kain kafan yang cukup. Jika ditutup kepalanya, kakinya terbuka. Jika ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Rasulullah ﷺ memerintahkan menutup kepalanya dan meletakkan daun idzkhir di kakinya.
Dari Sutra Mewah ke Kafan Tak Utuh
Rasulullah ﷺ bersabda lirih, mengenang masa lalu Mus’ab. Dulu, tak ada pemuda Makkah yang lebih halus pakaiannya, lebih lembut hidupnya. Hari ini, ia pergi menghadap Allah dengan dunia yang benar-benar ia tinggalkan. Uhud menjadi saksi: kemuliaan tidak diukur dari apa yang dikenakan, tetapi dari apa yang dikorbankan.
Kisah Mus’ab bukan nostalgia sejarah. Ia cermin yang ditaruh tepat di depan wajah kita. Di zaman ketika iman sering ditukar dengan kenyamanan, Mus’ab memilih luka. Ketika popularitas lebih dicari daripada kebenaran, Mus’ab memilih kesunyian dakwah. Ketika dunia menjanjikan sutra, Mus’ab memeluk kafan.
Ia tidak mati sia-sia. Ia hidup di setiap hati yang berani memilih Allah di atas segalanya. Ia hidup di setiap dakwah yang dilakukan dengan akhlak. Ia hidup di setiap pengorbanan yang tak terlihat kamera.
Dan mungkin, di saat kita merasa terlalu berat melepaskan sedikit kenyamanan demi agama ini, Uhud akan kembali berbisik:
Pernah ada seorang pemuda bernama Mus’ab bin Umair. Ia melepaskan segalanya—dan Allah mengabadikan namanya selamanya.
*Anda bisa lihat info lain di Instagram kami.